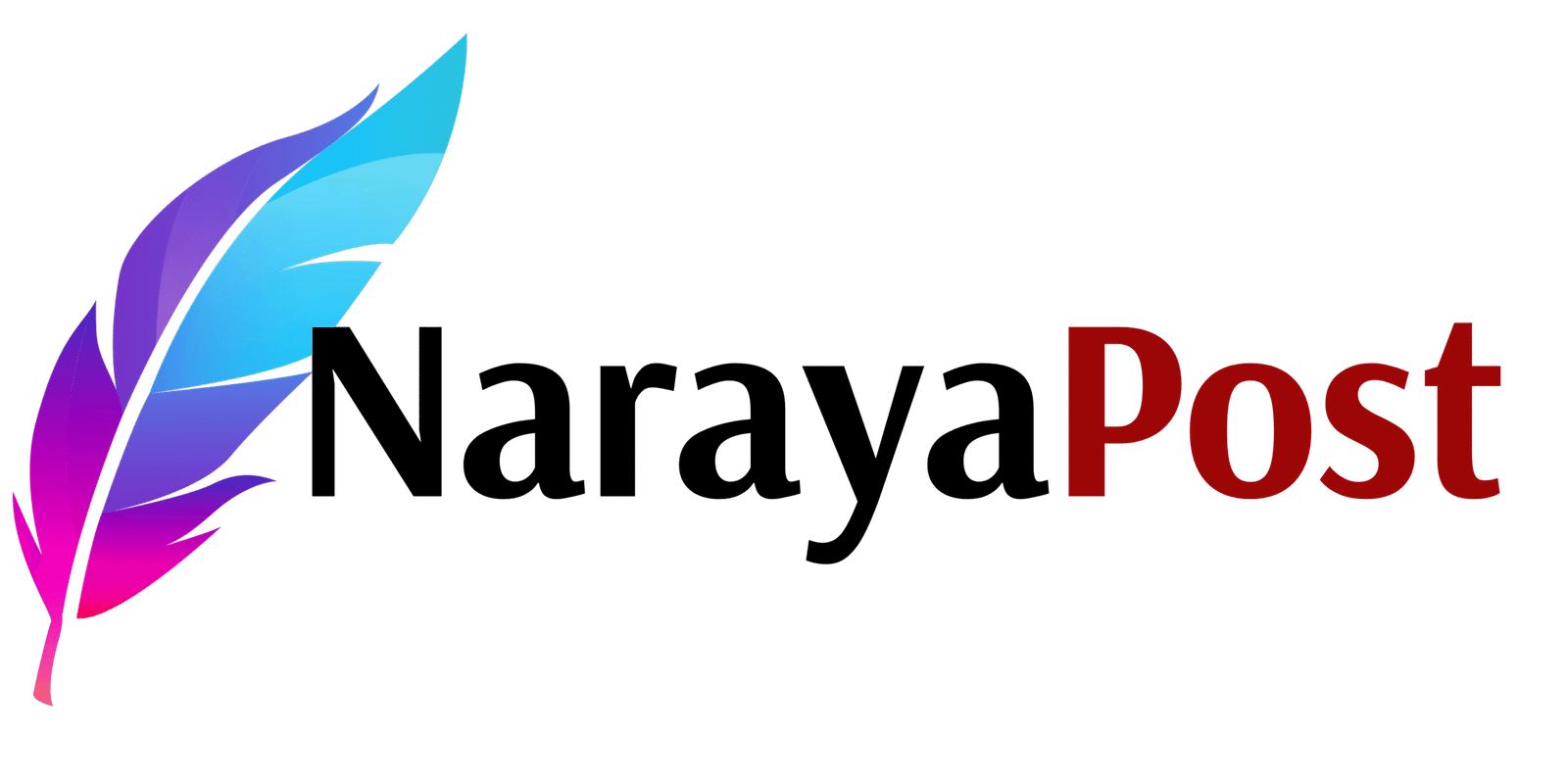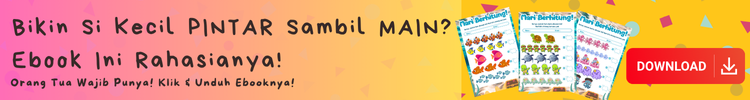Standar Garis Kemiskinan RI Meledak, Akankah Direvisi?

NarayaPost – Sorotan terhadap data kemiskinan nasional kembali mencuat ketika Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan usul agar metode perhitungannya segera diperbarui. Usulan ini berangkat dari perubahan standar garis kemiskinan global yang dirilis oleh Bank Dunia.
Kini, standar perubahan ini menggunakan metode Purchasing Power Parity (PPP) 2021, menggantikan versi sebelumnya PPP 2017. Atas langkah tersebut, jumlah angka kemiskinan di Indonesia melonjak drastis, menyentuh angka 194,6 juta jiwa.
“Penerapan PPP tahun 2021 menyiratkan adanya revisi terhadap garis kemiskinan global,” dikutip dari dokumen Bank Dunia berjudul ‘June 2025 Update to the Poverty and Inequality Platform (PIP)‘, yang telah dilakukan perubahan perhitungan dari paritas daya beli.
BACA JUGA: Muzani Ingatkan Menteri : Jangan Bebani Presiden Prabowo!
Luhut Akan Segera Lakukan Revisi
“Secara menyeluruh, hal ini sedang dikaji. Badan Pusat Statistik (BPS) juga sudah berdiskusi dengan kami terkait hal ini,” ujar Luhu di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Revisi standar garis kemiskinan bukan menandakan kondisi ekonomi memburuk, tetapi bagian dari proses penyesuaian data agar lebih akurat dan relevan dengan standar global. “Saya kira laporannya sudah kami siapkan untuk disampaikan kepada presiden, tidak ada yang aneh,” urainya.
Luhut menambahkan, revisi tengah dikerjakan oleh Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Prof. Arief Anshory Yusuf serta akan dibahas dalam rapat bersama. Bila nanti Presiden Prabowo menyetujui, sesegera mungkin angka kemiskinan baru akan diumumkan ke publik.
“Kita tidak perlu kaget-kaget, kita harap jika presiden setuju, angka-angka ini bisa segera keluar. Dengan begitu, nantinya bisa mencerminkan angka sebenarnya,” jelasnya. Pun, angka baru standar garis kemiskinan akan lebih mencerminkan kondisi riil masyarakat.
Menakar Standar Garis Kemiskinan dari Purcashing Power Parity (PPP)
PPP merupakan standar pengukuran untuk menentukan perbandingan biaya yang dibutuhkan untuk membeli suatu barang atau jasa yang sama di satu negara dengan negara lain, setelah nilai tukar disesuaikan.
Akan tetapi, nilai dollar AS yang digunakan pada PPP bukan kurs nilai tukar yang berlaku saat ini, tetapi paritas daya beli. Dengan adopsi PPP 2021, telah terjadi perubahan atas tiga lini garis kemiskinan. Dari semula ukuran tingkat kemiskinan ekstrem US$ 2,15 pada PPP 2017 menjadi US$ 3.00 berdasarkan PPP 2021.
Lalu, untuk garis kemiskinan negara berpendapatan menengah ke bawah (lower-middle income) dari US$ 3,65 menjadi US$ 4,20. Garis kemiskinan negara berpendapatan menengah ke atas (upper-middle income country/UMIC), seperti Indonesia di dalamnya, semula US$ 6,85 menjadi US$ 8,30.
Perubahan standar garis kemiskinan berdampak besar pada lonjakan jumlah penduduk miskin. Di Kawasan Asia Timur dan Pasifik, misalnya, jika menggunakan standar kemiskinan ekstrem sebesar US$ 3 PPP 2021, jumlah penduduk miskin melonjak menjadi 54 juta orang per Juni 2025. Padahal, standar sebelumnya yaitu US$ 2,15 PPP 2017, jumlahnya 20,3 juta orang per September 2024.
Sementara itu, dengan standar garis kemiskinan untuk negara berpendapatan menengah ke atas sebesar US$ 8,30 PPP 2021, jumlah penduduk miskin di kawasan yang sama turut meningkat signifikan, dari 584,2 juta jiwa menjadi 679,2 juta jiwa pada periode yang sama.
Penduduk Miskin Indonesia dalam Data BPS
Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2024, sebanyak 24,06 juta jiwa atau 8,57 persen dari total populasi masih hidup di bawah garis kemiskinan. Di balik angka itu, ada metode pengukuran cermat dan menggambarkan lebih dari sekedar nominal rupiah.
BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar atau Cost of Basicc Needs (CBN) untuk menentukan siapa yang tergolong miskin. Garis kemiskinan dihitung dari pengeluaran minimum seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun non-makanan.
Untuk konsumsi makanan, standar minimal ditetapkan sebesar 2.100 kilokalori per orang per hari disusun dari komoditas yang akrab di dapur rumah tangga Indonesia, seperti beras, telur, tempe, tahu, minyak goreng dan sayuran.
Sementara, kebutuhan non-makanan mencakup hal-hal penting dalam kehidupan sehari-hari seperti tempat tinggal, pendidikan, layanan kesehatan, pakaian hingga transportasi. Keseluruhan data dikumpulkan melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), dua kali dalam setahun.
Di tahun 2024 lalu, survei dilakukan bulan Maret, mencakup 345.000 rumah tangga dan September sebanyak 76.310 rumah tangga di seluruh penjuru negeri. Yang menjadi menarik, pengukuran kemiskinan dilakukan pada tingkat rumah tangga, bukan individu.
Dalam realitas di lapangan, kehidupan, pengeluaran hingga konsumsi umumnya dilakukan secara bersama. Sehingga, menggambarkan bagaimana keluarga telah menjadi unit utama dalam memahami kondisi ekonomi masyarakat di Indonesia.
Pakar Imbau Standar Garis Kemiskinan Lebih Disesuaikan
Dosen Program Studi Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (PSdK) FISIPOL UGM, Nurhardi menyatakan dukungan terhadap langkah ini. Menurutnya, garis kemiskinan yang digunakan sudah tidak relevan dengan realitas harga dan kebutuhan dasar masyarakat.
Selain itu, ada penyesuaian yang diperlukan agar data kemiskinan Indonesia selaras dengan standar internasional yang kini mengacu pada Purchasing Power Parity (PPP) 2021 yang diterapkan Bank Dunia. Ia mengingatkan, perubahan ini bukan sekadar teknis, tapi juga berdampak politis.
Pun, kekhawatiran utama adalah potensi lonjakan angka kemiskinan secara statistik. Jika Indonesia menggunakan kategori lower middle-income seperti standar Bank Dunia, angka kemiskinan bisa melonjak hingga 20 persen.
Bahkan, jika menggunakan kategori upper middle-income, jumlah bisa mencapai 60 persen. “Ini bisa menimbulkan persepsi negatif bahwa pemerintah gagal menanggulangi kemiskinan, padahal yang terjadi adalah perubahan metode pengukuran,” jelas Nurhadi dilansir dari laman resmi UGM.
Nurhadi menekankan, revisi ini harus dibarengi dengan strategi yang matang. Ia mengusulkan empat langkah utama. Pertama, pemerintah sebaiknya menggunakan standar moderat agar lonjakan angka kemiskinan tetap wajar dan dapat dikendalikan.
Kedua, proses transisi data harus dilakukan secara transparan dengan menyajikan dua versi data, versi lama dan baru agar publik bisa memahami konteks perubahan. Ketiga, perlu ada upaya komunikasi publik yang kuat, untuk menjelaskan bahwa kenaikan angka bukan karean kondisi ekonomi, tapi karena standar pengukuran yang lebih realistis.
Langkah keempat, menurutnya, adalah membedakan bentuk intervensi kebijakan antara kelompok miskin lama dan kelompok miskin baru. Kelompok miskin baru, yang muncul akibat perubahan garis ukur, sebaiknya lebih difokuskan pada program pemberdayaan ketimbang bantuan konsumtif.
Dirinya menegaskan bahwa pendekatan berbasis pemberdayaan sosial sangat penting. “Kita harus membantu masyarakat untuk bisa membantu dirinya sendiri. Bukan sekadar memberi bantuan, tapi membuka akses, membangun kapasitas, dan menciptakan peluang,” ujarnya.
Dalam konteks ini, Nurhadi juga menyoroti pentingnya peran lembaga seperti Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) yang telah menyusun Rencana Induk Pengentasan Kemiskinan Nasional.
BACA JUGA: Reza Pahlavi Serukan Dukungan Barat untuk Upaya Perubahan Rezim di Iran
Nurhadi memercayai bahwa integrasi antara pendekatan teknokratis dan politis akan menjadi kunci keberhasilan reformulasi garis kemiskinan di Indonesia. “Revisi ini adalah langkah maju. Namun harus dilakukan secara cermat, bijak, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Tujuan akhirnya tetap, keadilan sosial yang merata bagi seluruh rakyat,” pungkasnya.
Kesimpulan
Usulan revisi garis kemiskinan nasional yang disampaikan Luhut Binsar Pandjaitan muncul sebagai respons atas perubahan standar global dari Bank Dunia, yang kini menggunakan metode Purchasing Power Parity (PPP) 2021.
Perubahan ini berdampak besar terhadap lonjakan angka kemiskinan secara statistik, termasuk di Indonesia yang berpotensi mencatat angka hingga 194,6 juta jiwa jika menggunakan standar internasional terbaru.
Para pakar, seperti Nurhadi dari UGM, menyambut baik langkah ini namun menekankan pentingnya strategi yang cermat agar tidak menimbulkan persepsi keliru di masyarakat. Revisi perlu dilakukan secara transparan, komunikatif, dan pemberdayaan sosial yang adaptif.